BENCANA EKOLOGIS DI TENGAH KETIDAKPASTIAN AKIBAT PERANG (Bagian 3)
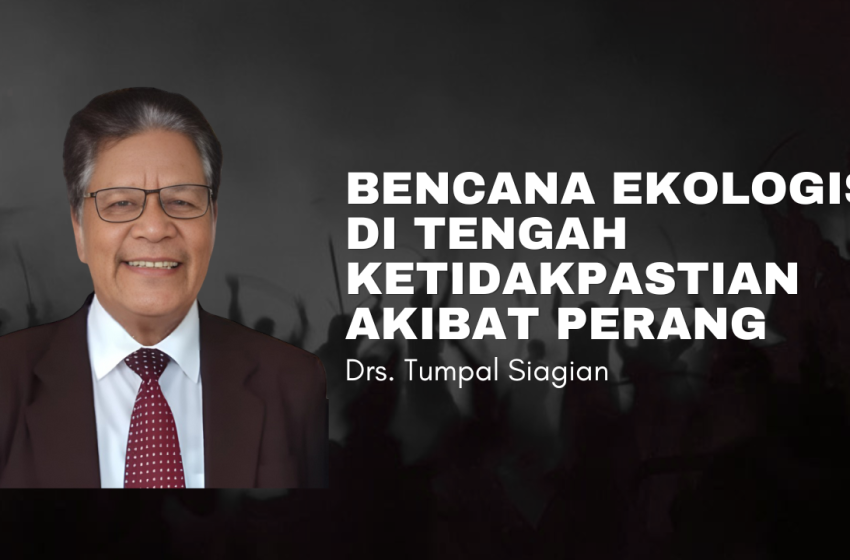
Penulis: Drs. Tumpal Siagian. Warga HKBP Duren Sawit
Pembiaran eksploitasi SDA tambang terlihat jelas pada hilirisasi nikel di Morowali- Halmahera, Maluku Utara memicu bencana ekologis sekaligus mempertontonkan tragedi administrasi dan pengawasan yang melempem. Isu yang seharusnya bisa disikapi secara jernih, yakni bertumpu pada kelestarian lingkungan serta masyarakat adat sebagai penjaga alam, kini berakhir dengan bencana ekologis.
Kita tahu, bahw nikel menjadi salah satu komponen utama untuk baterai yang dibutuhkan untuk mobil listrik dan komponen alat energi terbarukan, misalnya kincir angin.
Tetapi, harus diingat tambang nikel tersebut bukan jalan ekonomi berkelanjutan melainkan telah berdampak pada kerusakan dan bencana lingkungan hidup. Hal serupa terjadi di Raja Ampat Papua Barat Daya. Isu lingkungan yang viral dengan tagar #SaveRajaAmpat itu menyerukan agar publik tak tinggal diam melihat potensi kehancuran salah satu kawasan terumbu karang laut paling kaya di dunia karena ada tambang nikel disana. Pengakuan dunia UNESCO Global Geopark atas Raja Ampat pada 2023 mestinya menjadi titik tolak bagi Indonesia untuk memimpin konservasi laut tropis global dengan mencabut izin tambang di pulau-pulau sekitarnya.
Untuk itu perlu ada konsistensi atas pencabutan 4 (empat) izin usaha pembangunan (IUP) harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap tambang yang masih beroperasi di Gag, yang berada di pulau kecil dengan status hutan lindung.
Demikian pula di Wawonie di Sulawesi Tenggara yang merupakan pulau kecil dengan masalah tambang nikel. Kehadiran tambang dimaksud membawa banyak dampak buruk, gunung dikeruk, tanahnya diambil, lingkungan rusak,sungai dipenuhi lumpur,serta wilayah hutan yang dijaga masyarakat adat turun temurun kian terbuka.
Hal itu menunjukkan pengambilan kebijakan di Indonesia acapkali didasarkan pada kepentingan sesaat atau jangka pendek. Seharusnya, setiap kebijakan tata kelola tambang didukung analisis mendalam, termasuk terkait aspek ekonomi, hukum,dan lingkungan ke depan. Aspek regulasi harus menunjukkan aspek kepastian hukum sehingga pelaku usaha pun tidak dirugikan. Dari sisi perencanaan dan investasi, para pelaku usaha dapat merancang operasional, cash flow, termasuk pembangunan infrastruktur dan hilirisasi. Jangan sampai pemegang IUP mendadak harus dihentikan aktivitasnya karena dituding bisa membahayakan sekaligus menimbulkan potensi rusaknya lingkungan.
Tanpa peninjauan ulang, Indonesia bisa terjebak dalam kontradiksi antara retorika hijau dan praktik abu-abu. Praktik ekonomi kapitalistik dan ekstraktif yang tak berkeadilan bersenyawa dengan perilaku elite politik yang korup.
Bukan sekadar berapa ton logam ton nikel yang diambil, tetapi putusnya ikatan antarmanusia dengan tanah, laut, dan budaya yang merupakan eksistensi bangsa. Para pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk menentukan arah pariwisata Raja Ampat agar terjadi keseimbangan ekonomi dengan dampak sosial dan lingkungan yang muncul. Hal ini menggambarkan, ada “perang” antara visi kepentingan jangka pendek (IUP) dan visi jangka panjang (perlindungan keaneragaman hayati dan pariwisata). Hal itu juga mengggambarkan spektrum “perang” antara kerakusan/ ketamakan/ keserakahan versus kecintaan pada lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim.
Dalam tingkat global perubahan iklim telah memicu pelbagai bencana ekologis. Selain deforestasi dan degradasi hutan serta diperparah perubahan lahan yang dialihfungsikan untuk perkebunan, industri manufaktur, dan permukiman.
Bahkan, ditengarai pemakaian energi fosil berbasis minyak bumi dan batubara jadi penyumbang tertinggi terjadinya perubahan iklim secara global.
Lingkungan hidup berada di bawah ancaman agenda transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ironis memang. Transisi energi yang pada esensinya bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan hidup, justru menjadi ancaman baru bagi keberlanjutan dan deringkan alarm ekosida.
Transisi energi menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dan eksistensi bangsa. Konflik kepentingan pun mengikutinya antara perlindungan masyarakat adat yang rentan miskin dengan pemilik komoditas kapital. Keserakahan pada berhala kekuasaan dan kepemilikan harta yang diraih melalui praktik korupsi pun terjadi.Hal ini sesungguhnya merefleksikan peenyelenggaraan negara dengan tata kelola pemerintahan yang buruk,turut memperkeruh situasi.
Karena itu, PSN tata kelola tambang harus melewati persyaratan ketat, dimulai dari tahap perencanaan, melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang dikerjakan pakar independen, bukan akademisi bayaran karena PSN bukan proyek bebas hambatan.
Berdasarkan agenda prioritas Presiden Prabowo dengan Astacitanya dalam menuju pola negara kesejahteraan (Welfare-State) yang menjadikan rakyat sebagai titik tolak program-program pembangunan merupakan refleksi amanat perjuangan kemerdekaaan para pendiri negeri ini. Para pendiri negeri telah menegaskan bahwa negara-bangsa bernama Indonesia dibentuk untuk mengupayakan terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi segenap penduduknya.
Tetapi,dengan postur alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terbatas dan Utang yang harus dijaga,pengelolaan PSN perlu menerapkan pola kolaboratif sejak perencanaan yakni keberimbangan pembiayaan publik dan keterlibatan Swasta. merupakan kebutuhan struktural agar proyek-proyek strategis tetap berkelanjutan tanpa membebani anggaran. Jangan sampai adagium Karl Marx yang mengatakan, “history repeats itself, first as tragedy, second as farce” (sejarah berulang dengan sendirinya, pertama sebagai tragedi, kedua sebagai lelucon).


