BENCANA EKOLOGIS DI TENGAH KETIDAKPASTIAN AKIBAT PERANG (Bagian 2)
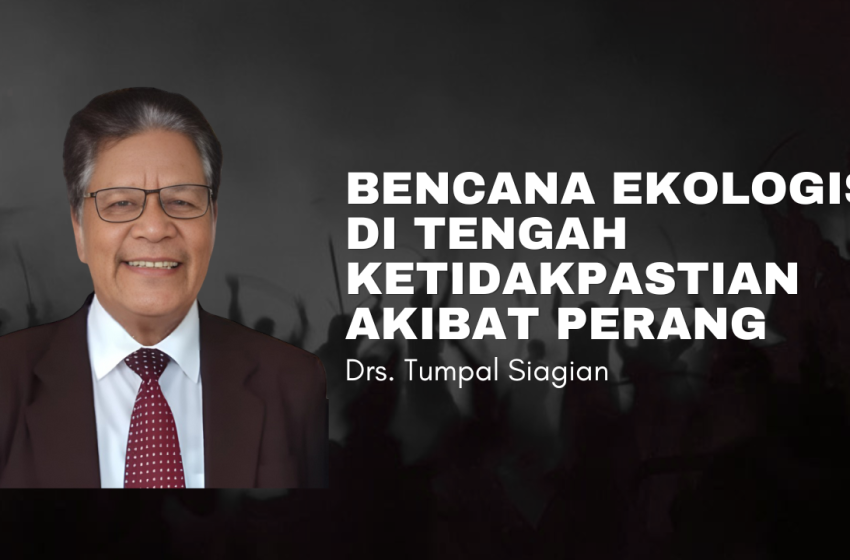
Penulis: Drs. Tumpal Siagian. Warga HKBP Duren Sawit
Tindakan Trump dalam perseteruan “perang dagang” China-AS hanyalah riak di permukaan. Dinamika dibawahnya adalah perlombaan untuk supremasi pada transisi energi.
Perubahan iklim merupakan pendorong utama transisi energi dari energi berbasis fosil ke energi baru dan terbarukan atau EBT.
Beberapa faktor yang membuat transisi energi lebih mendesak, yaitu peningkatan gas rumah kaca, kenaikan permukaan air laut akibat melelehnya es di kutub utara dan selatan, peningkatan suhu lautan, serta peningkatan keasaman lautan.
Dunia bertransformasi dan beradaptasi pada modernitas memuliakan lingkungan hidup di tengah peradaban teknologi hijau. Ketahanan energi dalam EBT tampak terlihat di persaingan pada rantai pasok tanah langka (rare earth materials). Tekonologi hijau membutuhkan tanah langka, termasuk magnet, seperti neodymium, dan samarium cobalt, yang digunakan untuk kendaraan listrik, turbin angin perangkat audio dan video, hard-disk komputer, dan lainnya.
Konsekwensinya, apa pun yang dianggap menuju keadidayaan era EBT pada perseteruan AS – China dapat dijadikan alat tawar-menawar. Belajar dari perang tarif AS – China, mengajarkan kepada kita bahwa EBT tidak hanya merupakan bentuk ketahanan (security) tetapi juga menjadi suatu kekuatan tawar (leverage) dalam menghadapi fragmentasi rantai pasok energi global dan perubahan aliansi geopolitik. Ketegangan geopolitik dan transisi ke EBT akan berimbas pada upaya/ konsistensi setiap negara dalam menurunkan emisi, termasuk bagi Indonesia.
Konsistensi ini penting agar tidak terjadi paradoks antara kampanye global tentang iklim dan kebijakan dalam negeri yang masih permisif terhadap industri ekstraktif.
Menjaga lingkungan hidup berarti menghentikan industri ekstraktif, menegakkan keadilan sosial, serta penghormatan terhadap lingkungan hidup adalah perjuangan/ikhtiar tanpa akhir.
Industrialisasi merupakan pendorong utama pertumbuhan negara-negara di dunia. Beberapa negara di Asia mengalami pertumbuhan signifikan melalui jalur ini. Sebut saja, Jepang, Korea Selatan, dan China yang saat ini berstatus negara maju.
Kondisi China sebenarnya serupa dengan Indonesia dalam aspek sumber daya alam (SDA). Pengalaman China menjadi negara industri terbesar di dunia dimulai lewat pengembangan industri pengolahan besi dan baja, kimia, smelter bahan tambang, batu bara, dan permesinan. Pengembangan sains dan teknologi memberikan fondasi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kemakmuran bangsa itu. Dengan memiliki stok SDM dengan kemampuan teknis yang sangat memadai menjadi kunci industri maju.
Berkaca dari China, kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa tidak terjadi dengan sendirinya. Indonesia harus memiliki fondasi yang lebih kuat dalam mengelola dan memanfatkan SDA agar tetap memberi manfaat dan lebih diminati untuk investasi di sektor industri lanjutan.
Namun, karena pemangku kepentingan seringkali rapuh dan mudah runtuh pada godaan keserakahan, dan ketamakan, maka republik ini harus membayar harga yang mahal bagi sistem politik dan ekonomi kita. Praktik korupsi merajalela di tengah mayoritas rakyat miskin, merefleksikan penyelenggara negara yang tidak tansparan,dengan tata kelola yang buruk. Bahkan, menurut peraih Nobel Ekonomi 2001, Joseph Stiglitz dalam The Price of Inequality (2012), “sistem ekonomi kita terlihat gagal untuk menyejahterakan bagi sebagian besar rakyat karena sistem politik kita dikuasai oleh kepentingan uang”.
Refleksi Tata Kelola Tambang dan Transisi Energi
Bumi Indonesia diberkati dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) dan keindahan alam bagi pariwisata. Kawasan Danau Toba di Sumatera Utara dan Raja Ampat di Papua Barat sudah ditetapkan Taman Bumi atau “Geopark” oleh UNESCO Global Geopark. Oleh karena itu, pemerintah perlu memegang teguh prinsip sustainable investment, responsible investment atau green investment di kedua geopark tersebut. Artinya, kendati menguntungkan secara komersil seperti kasus keramba jaring apung di Danau Toba dan tambang nikel pada pulau-pulau kecil di Raja Ampat tetapi sangat sensitif terhadap degradasi lingkungan dengan dampak sosial dan bencana ekologis yang muncul serta-merta ikut memicu krisis iklim.
Krisis iklim berdampak pada cuaca ekstrem, bencana hidrometeorologi, kelangkaan sumber daya air, kegagalan panen, penurunan produksi pangan, dan penyebaran penyakit menular. Semua itu ikut menurunkan kualitas hidup.
Anomali cuaca ekstrem akibat krisis iklim terjadi di berbagai belahan dunia. Banjir dan hujan deras saat musim kemarau terjadi di sejumlah negara seperti di Tokyo, Jepang, Beijing China, dan di Texas, Amerika Serikat. Sementara di Eropa,seperti di Inggris, Perancis, Italia, Yunani dan Jerman gelombang panas melanda. Suhu muka laut di Samudera Hindia dan Pasifik barat lebih panas daripada biasanya. Suhu permukaan bumi terus meningkat. Implikasinya, cuaca ekstrem terus terjadi seperti bencana banjir bandang melanda kawasan Jabodetabek di Pulau Jawa, sedangkan panas ekstrem mendera kawasan Toba di Sumatera Utara.
Panas ekstrem berdampak besar dan menimbulkan resiko besar akan kebakaran lahan dan hutan.
Kebakaran lahan dan hutan terkini terjadi di sejumlah daerah di kawasan Danau Toba. Api muncul dipicu kemarau melahap kawasan hutan di Pangururan Tele dan Pusuk Buhit, Samosir hingga di hutan Tongging, Tanah Karo dan kawasan Sibaganding, Simalungun.
Selain faktor musim kemarau, sebagian besar kebakaran lahan dan hutan terjadi akibat warga mempersiapkan lahan pertanian dengan cara membakar. Padahal, warga yang membuka lahan dengan cara membakar sangat berbahaya dan bisa dijerat sanksi pidana.
Dengan perubahan iklim yang kian nyata, Indonesia perlu berkomitmen meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi. Bersama negara lain, seperti AS, China, dan Uni Eropa penyumbang terbesar emisi, Indonesia mesti mengupayakan penurunan emisi global untuk menjaga kenaikan suhu permukaan Bumi. Tingginya emisi global ditengarai sebagai akibat penggunaan energi fosil yang masih mendominasi.
Hampir semua wilayah Indonesia menyimpan kekayaan SDA. Untuk mempercepat proyek-proyek lintas sektor yang dianggap vital bagi transformasi ekonomi nasional dirancang Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek besar yang mencakup infrastruktur dasar, konektivitas digital, hilirisasi tambang, dan penguatan kawasan strategis.
Ironisnya, nyaris di semua sudut pula kita melihat atau menemukan jejak praktik eksploitasi SDA seperti tambang ilegal. Hal ini mempertanyakan biaya sosial dan ekologis industri ekstraktif yang merusak lingkungan. Mereka tidak lagi menghargai harkat dan martabat warga lokal penghuni SDA. Mereka hadir seperti parasit, merusak ekosistem, menggusur ruang hidup warga, hingga menyulut bencana. Tambang ilegal bukan sesuatu yang baru/ dadakan muncul, melainkan sistematis, terstruktur, dan sudah berlangsung lama dalam waktu yang panjang.
Di lain pihak, tata kelola tambang di daerah sangat rentan disusupi maladministrasi, kelalaian prosedural, dan bahkan indikasi korupsi. Maladministrasi bukan sekadar kelalaian administratif belaka, melainkan sering menjadi pintu masuk dari praktik korupsi secara sistematik.
Korupsi di sektor pertambangan bukan sekadar korupsi uang negara, tetapi kebijakan yang koruptif yang terselubung/tersembunyi dalam regulasi dan kelonggaran sistem menjadi taruhan terjadinya ekosida hanya karena kepentingan pragmatis dan keuntungan sepihak. Kita tidak boleh membiarkan eksploitasi SDA tersembunyi di balik pertumbuhan ekonomi.
(BERSAMBUNG)


