BENCANA EKOLOGIS DI TENGAH KETIDAKPASTIAN AKIBAT PERANG (Bagian 1)
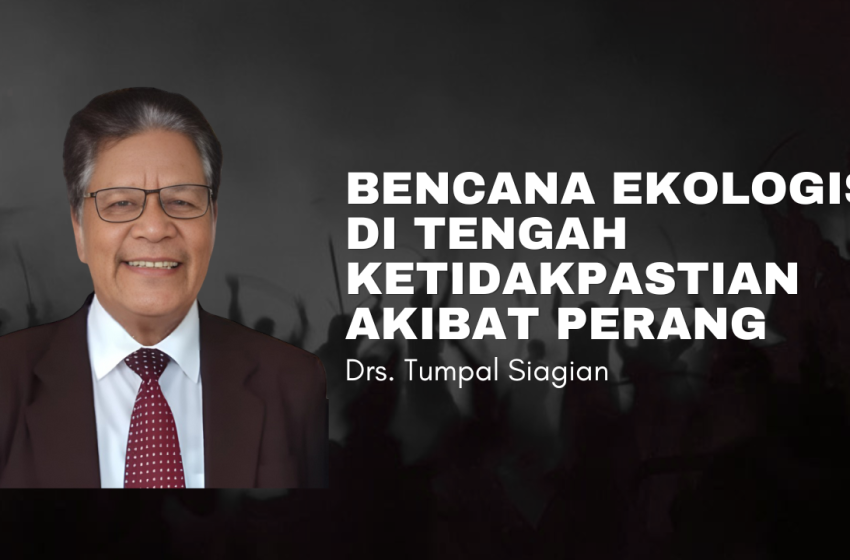
Penulis: Drs. Tumpal Siagian. Warga HKBP Duren Sawit
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi (Kejadian 1:1)
Ketika Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden, Allah memberi keleluasaan atau kuasa kepadanya untuk mengelola dan memanfaatkan alam ini (Kejadian 1: 25-31). Dan, manusia ditugaskan untuk mengusahakan dan memeliharanya (Kej.2:15). Artinya, manusia harus bisa merawat dan memelihara agar selalu baik, seperti ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Sebab,alam semesta adalah anugerah Tuhan. Allah sendiri berkata kepada manusia, “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”(Kejadian 1:28).
Refleksi hubungan Allah dengan ciptaanNya harus dipahami sebagai anugerah untuk mengusahakan dan mengelola alam semesta dengan baik. Manusia bertanggung-jawab untuk merawat dan melindunginya serta menjaga keseimbangannya.
Dengan status dan fungsinya seperti itu, manusia tidak hanya diciptakan segambar dengan Allah (Imago Dei) tetapi manusia dipercaya menjadi perpanjangan tangan Allah dalam melakukan tugas menjaga lingkungan hidup alam semesta ini. Tuhan menghendaki agar manusia mengusahakan pemenuhan hak hidup yang merupakan tanggung jawab ekologisnya.
Tetapi apa yang terjadi?
Manusia yang diciptakan Allah itu bertindak sewenang-wenang terhadap alam dengan berbagai permasalahannya. Perilaku eksploitatif manusia terhadap sumber daya alam sesungguhnya merupakan bentuk penodaan dan perusakan terhadap karya agung Allah. Alam hanya dilihat pada fungsinya sebagai pemenuh kebutuhan manusia kendati usahanya itu menimbulkan bencana ekologis.
Bumi terguncang oleh emisi karbon, deforestasi, kerakusan energi, dan perang. Baik perang militer, perang ekonomi, perang keuangan dan bahkan perang dagang antar negara.
Perang militer antar negara membawa derita tak terperi, terutama yang menimbulkan extreme human suffering dan juga innocent death banyak sekali. Sejak Perang Dunia I dan II dimana setiap bom atau roket yang ditembakkan tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi ada derita lain yang kerap dilupakan, yaitu luka bumi. Luka bumi yang tidak gampang disembuhkan. Bumi terluka, betul-betul kesakitan. Manusia yang menghuninya terdampak. Ekosistem hancur, sungai beracun, udara tercemar, serta tanah menjadi gersang kehilangan daya hidup. Itulah ekosida, yaitu kehancuran kelangsungan hidup yang kehancurannya memicu lonjakan emisi. Ekosida, suatu slogan kerusakan lingkungan yang bertautan dengan perang melintasi zaman.
Perkembangan seusai Perang Dingin (dekade 1990-an) menyeruak optimisme tentang tata hidup dalam era globalisasi yaitu dunia yang saling terhubung dan tak lagi tersekat akan batas-batas negara-bangsa (nation-state) untuk menopang keberadaan manusia.
Pada 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menginisiasi dan mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan ini menjadi seruan bersama untuk mendorong aksi mengakhiri kemiskinan, melindungi Bumi, dan menjadi warga dunia mencapai perdamaian dan kemakmuran pada 2030. PBB juga memfasilitasi perjanjian internasional dan permodalan bagi negara berkembang.
Namun, dunia terus bertingkah dan perang tak berkesudahan membuat permasalahan semakin kompleks.
Konflik bersenjata meruncing dan tak kunjung usai. Konflik Rusia-Ukraina sejak 2022, dan Israel- Hamas/ Palestina sejak 2023 yang menyeret Hizbullah/ Lebanon, Iran, dan melibatkan Amerika Serikat (AS).
Teranyar, deru perang Israel-Iran pada Juni 2025 menghentak dan mengejutkan dunia. Israel menyasar instalasi pengayaan nuklir Iran dan Iran pun melakukan serangan balasan menembakkan rudal Iran ke Israel. Deru perang Israel-Iran, tidak hanya menghancurkan bangunan, infrastruktur, tetapi juga lingkungan hidup memicu lebih banyak lagi lonjakan emisi.
Bumi menghadapi ancaman yang nyata, jika tidak diatasi secara serius. Ternyata, di era modern seperti saat ini, perang pun bertransformasi menjadi “perang dagang” untuk meraih keuntungan.
Perang dagang yang eskalatif dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit di semua segi kehidupan.
Ptoteksionisme dan orientasi “inward looking” serta prinsip “my country first” telah mengancam dan menghancurkan kerjasama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia II; yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara Barat dalam hal ini AS, membuat situasi global sangat tidak stabil (volatile) dan kompleks.
Perang dagang (trade war) AS-Cina dengan Kebijakan tarif resiprokal Trump terhadap negara mitra dagang AS, menandai bangkitnya politik domestik yang mengutamakan kepentingan nasional di atas dinamika keterhubungan global.
Harapan akan tatanan global yang lebih inklusif, tak lagi didikte oleh satu kekuatan dominan, mengemuka dengan kemunculan kelompok BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan dengan negara-negara Belahan Bumi Selatan (Global South) lainnya di kancah perdagangan internasional. Upaya BRICS membangun institusi keuangan tandingan dengan New Development Bank (NDB), yang disebut-sebut sebagaj penantang Bank Dunia (World Bank). Sejauh ini, BRICS memperluas keanggotaannya hingga 10 negara, termasuk Indonesia menjadi anggota penuh di dalamnya tidak otomatis memperluas pengaruh. Sebab, tanpa visi strategis yang jelas, koordinasi yang lebih erat, dan solusi yang nyata,sejumlah pengamat menilai BRICS berisiko menjadi sekadar klub simbolik darpada kekuatan yang mampu mengubah sistem global.
Namun, perang dagang AS-China akan memberikan efek domino pada sektor energi dan memunculkan ketidakpastian pula terkait komitmen negara-negara dalam menurunkan emisi. Ketegangan akibat perang dagang pun dapat memengaruhi agenda aksi iklim dan transisi energi secara global, dan akan berdampak pula pada rantai pasok global untuk teknologi bersih. Kebijakan tarif Trump diyakini tidak hanya berdampak terhadap perekonomian, tetapi juga berdampak pada aspek lain, seperti “perang” dalam persaingan supremasi sains dan teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan lingkungan hidup yang menjadi kekuatan daya saing atau keadidayaan suatu negara.
Sains, teknologi, dan inovasi adalah pilar pertumbuhan ekonomi, yakni memanfaatkan sebaik-baiknya kualitas SDM di bidang sains, teknologi, enqineering, dan matematik (STEM).
Untuk memperkuat ekosistem inovasi di sektor pertambangan misalnya adalah sangat penting membangun kemitraan strategis pengembangan sains dan teknologi berkolaborasi dengan lingkungan hidup sebagai jembatan antara dunia riset dan industri guna mendorong pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset secara optimal.
(BERSAMBUNG)


